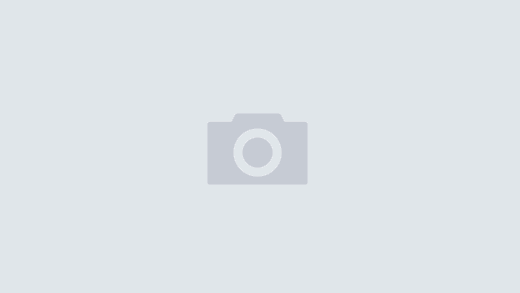Di sebuah biara Katolik yang tenang, para biarawan hidup dalam disiplin doa, kerja, dan kontemplasi. Setiap malam, mereka berkumpul di kapel untuk ibadat malam, mendoakan kedamaian dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, ketenangan doa mereka kerap terganggu oleh seekor kucing kecil yang tinggal di biara.

Kucing ini, bernama Si Belang, memiliki kebiasaan mengeong keras setiap kali para biarawan mulai berdoa. Suaranya yang lantang sering kali menggema di kapel, membuat para biarawan yang sedang khusyuk menunduk kepala saling melirik, mencoba menahan senyum.
Akhirnya, kepala biara memutuskan untuk mengatasi masalah ini. “Mulai sekarang, setiap malam, kucing itu harus diikat di luar kapel sebelum ibadat dimulai,” katanya dengan tenang. Para biarawan setuju, dan sejak saat itu, tradisi mengikat kucing sebelum ibadat malam menjadi rutinitas.
Tradisi ini berlangsung lama, bahkan setelah kepala biara yang bijak itu meninggal dunia. Ketika Si Belang akhirnya mati karena usia tua, para biarawan merasa perlu menggantikannya dengan kucing baru. Mereka percaya bahwa kehadiran kucing—yang diikat selama ibadat—merupakan bagian penting dari tradisi mereka.
Namun, keusilan kucing tidak berhenti di situ. Pada saat doa makan di ruang makan biara, ketika para biarawan menundukkan kepala dan mengucapkan doa syukur, kucing baru ini, yang sama cerdiknya, sering mencuri ikan dari meja makan. Para biarawan, yang membuka mata setelah doa, hanya bisa saling memandang bingung sambil melihat piring yang sudah kosong. Kucing itu duduk santai di sudut ruangan, menjilati mulutnya dengan puas.
“Apakah ini ujian kesabaran?” gumam salah seorang biarawan, mencoba memahami kejadian itu.
Melihat ini, kepala biara yang baru tersenyum dan berkata, “Mungkin Tuhan mengingatkan kita bahwa doa yang sempurna adalah doa yang juga melibatkan tindakan. Kita perlu memperhatikan sekitar, bukan hanya menutup mata.” Sejak saat itu, para biarawan mulai menyediakan seporsi kecil makanan untuk kucing sebelum makan bersama. Dengan begitu, kucing tidak lagi mencuri makanan, dan suasana makan menjadi lebih damai.
Lama kelamaan, tradisi ini berkembang. Para biarawan mulai memandang kucing sebagai simbol kesederhanaan dan kebersamaan. Mereka bahkan memasukkan doa khusus untuk “semua makhluk ciptaan Tuhan” dalam ibadat mereka. Generasi biarawan berikutnya meneruskan tradisi ini, bahkan tanpa memahami alasan awalnya.
Berabad-abad kemudian, tradisi mengikat kucing dan menyediakan makanan khusus untuknya menjadi subjek kajian teologis. Para biarawan mulai menulis tafsir tentang “kehadiran kucing dalam doa.” Salah satu kitab bahkan diberi judul Kebijaksanaan Kucing dan Spiritualitas Biara.
Namun, seperti biasa, ada satu biarawan muda yang kritis. “Mengapa kita masih mengikat kucing sebelum ibadat malam, padahal kucing ini tidak mengeong seperti dulu?” tanyanya.
Kepala biara yang bijak menjawab sambil tersenyum, “Tradisi itu indah, tapi lebih indah lagi jika kita memahami maknanya. Kita harus bertanya: apakah kita melakukan ini untuk menghormati Tuhan atau hanya karena kebiasaan?”
Terinspirasi dari tulisan Anthony de Mello, SJ dalam buku Burung Berkicau (Yayasan Cipta Loka Caraka, Cetakan 7, 1994).
KUCING SANG GURU
Setiap kali guru siap untuk melakukan ibadat malam, kucing asrama mengeong-ngeong, sehingga mengganggu orang yang sedang berdoa.
Maka ia menyuruh supaya kucing itu diikat selama ibadat malam.Lama sesudah guru meninggal, kucing itu masih tetap diikat selama ibadat malam.
Dan setelah kucing itu mati, dibawalah kucing baru ke asrama, untuk dapat diikat sebagaimana biasa terjadi selama ibadat malam.Berabad-abad kemudian kitab-kitab tafsir penuh dengan tulisan ilmiah murid-murid sang guru, mengenai peranan penting seekor kucing dalam ibadat yang diatur sebagaimana mestinya.